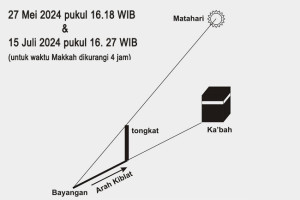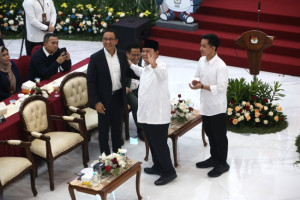Yogyakarta, Gatra.com - Dunia maya dihebohkan oleh film ‘Tilik’ yang menampilkan kisah ibu-ibu yang bergosip, terutama oleh tokoh sentralnya, Bu Tejo. Film ini menampilkan realitas dan stigma perempuan, ketimpangan literasi digital, dan budaya ‘ghibah’ di sekitar kita.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada Wahyu Kustiningsih menjelaskan film yang berbahasa Jawa dan menampilkan budaya ‘tilik’ atau menjenguk orang sakit ini terasa dekat masyarakat desa, terutama di Jawa.
“Tilik ini budaya lokal yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat. Minimnya alat transportasi massa membuat mereka akhirnya menyewa truk melalui iuran bersama,” kata Wahyu saat dihubungi Gatra.com, Kamis (20/8).
Menurutnya, film produksi Ravacana Films dari Yogyakarta ini meneguhkan kekuatan modal sosial masyarakat perdesaan yang penuh kekeluargaan dan gotong royong.
Film berdurasi 32 menit besutan Wahyu Agung Prasetyo itu juga menunjukkan kehadiran teknologi internet yang belum disertai kapasitas atau daya literasi digital yang memadai pada masyarakat perdesaan.
“Hingga akhirnya memunculkan kesimpangsiuran informasi yang berkontribusi pada beredarnya informasi yang tidak tervalidasi atau hoaks,” kata pengajar di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini.
Menurutnya, mayoritas perempuan desa di film ini digambarkan sebagai individu yang menerima secara mentah informasi di internet. “Dengan kata lain, film ini menegaskan bahwa kapasitas literasi digital pada perempuan desa masih rendah,” Imbuhnya.
Tak kalah penting, Wahyu menjelaskan, film ini menyuarakan beban-beban sosial dan stereotip yang dilekatkan pada perempuan, yakni pada Dian, karater kembang desa di film ini.
”Segala pencapaian ‘sukses’ secara materi oleh Dian seringkali dicap melalui proses yang negatif bagi seorang perempuan. Sayangnya, film ini seolah memberikan pembenaran atas stereotip tersebut khususnya ketika di adegan akhir,” kata dia.
Di bagian itu, menurut Wahyu, film ini cenderung bersifat misoginis dengan menempatkan perempuan sebagai objek kebencian melalui kekerasan verbal yang parahnya diamini oleh sesama perempuan lainnya.
Wahyu juga menyoroti perilaku bergosip atau kini lumrah disebut ‘ghibah’ atau julid yang seringkali dilekatkan pada perempuan dan semakin memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan.
“Bu Tejo menjadi sosok Ratu Gosip yang ucapannya diamini oleh ibu-ibu lainnya yang kebetulan memiliki kuasa pengetahuan dan sumber daya lebih rendah,” kata dia.
Dalam beberapa studi, Wahyu menjelaskan, gosip dipandang sebagai sesuatu yang positif. Antropolog sekaligus psikolog Oxford University, Robert Dunbar, dalam bukunya “Grooming, Gossip, and the Evolution of Language”, menyebut gosip berperan dalam tatanan dan kohesi sosial untuk merekatkan relasi sosial.
“Dalam sejarah kehidupan manusia, gosip berperan sebagai strategi untuk menemukan solusi secara bersama atas persoalan yang sedang dihadapi,” kata dia.
Pada perkembangannya, manusia bergosip dengan tujuan untuk tetap terkoneksi satu sama lain dan praktik ini tidak mudah tergantikan dengan hadirnya teknologi komunikasi.
“Gosip dianggap sebagai aktivitas mengasyikkan karena ada pertukaran informasi atas orang yang berada di jejaring sosial kita,” ujarnya.
Meski secara moral dinilai negatif, melalui studinya, sosiolog Stanford University, Robb Willer, menemukan bahwa gosip dapat digunakan sebagai alat untuk mereformasi kelompok pengganggu, menggagalkan eksploitasi pada “orang baik”, dan mendorong kerjasama.
“Studinya menyebutkan bahwa kelompok yang membiarkan gosip di dalamnya cenderung dapat mempertahankan kerjasama dan menekan keegoisan individu," katanya.
Gosip juga membuat individu belajar tentang perilaku orang lain. Informasi terkait perilaku tersebut juga digunakan menjalin kerjasama dengan individu lain yang dianggap selaras.
Pada masyarakat yang sangat mementingkan reputasi, gosip menjadikan seseorang dapat berperilaku pro-sosial dan cenderung lebih murah hati karena tidak ingin dikucilkan. “Dengan kata lain, gosip berkontribusi dalam kontrol atas norma sosial di masyarakat,” kata Wahyu.